Pengantar
Salah satu pemikiran Durkheim yang cukup terkenal adalah teori tentang agama. Menurutnya, “agama merupakan sesuatu yang benar-benar bersifat sosial.”Kepercayaan dan ritual-ritual keagamaan, bagi Durkheim, merupakan ungkapan simbolik dari realitas sosial. Realitas sosial itu mendahului realitas agama. Ia menjiwai, melatarbelakangi, dan melahirkan realitas-realitas keagamaan. Nah, dalam paper ini, penulis akan membahas secara panoramik mengapa dan bagaimana realitas sosial tersebut hadir dan mewujud dalam agama. Pembahasan dalam paper ini akan didasarkan pada kajian Durkheim tentang bentuk dasar dari agama suku (totemisme), termasuk juga analisanya tentang pemisahan Yang Sakral dan Yang Profan, yang terekam dalam buku “The Elementary Forms of the Religious Life.”
Yang Sakral dan Yang Profan
Pemisahan antara Yang Sakral dengan Yang Profan merupakan hal yang mendasar dalam analisis terhadap agama. Hal-hal Yang Sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, dalam kondisi normal tidak tersentuh, dan selalu dihormati. Sebaliknya, hal-hal Yang Profan adalah bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja. Dan, konsentrasi utama terletak pada hal Yang Sakral. Sebagimana Durkheim menulis:
“Semua kepercayaan religius, yang sederhana maupun yang kompleks, memperlihatkan satu ciri umum, yaitu mensyaratkan pengklasifikasian antara yang sakral dengan yang profan ….. Hal-hal yang sakral adalah hal-hal yang dilindungi dan diisolasi oleh larangan-larangan; hal-hal yang profan adalah hal-hal tempat larangan-larangan itu diterapkan dan harus dibiarkan berjarak dari hal-hal yang sakral.”
Dengan demikian, dunia Yang Sakral merupakan bagian terpisah dari dunia Yang Profan. Yang Profan tidak dapat memasuki dunia Yang Sakral. Karena, apabila Yang Profan dapat memasuki dunia Yang Sakral, maka Yang Sakral tersebut akan kehilangan arti kesakralannya. Misalnya saja, sebuah gedung gereja akan nampak kesakralannya ketika gedung gereja tersebut hanya difungsikan sebagai tempat beribadah, tempat orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Akan tetapi, ketika gedung gereja tersebut beralih fungsi menjadi tempat perbelanjaan atau kantor, maka kualitas sakral yang sebelumnya disematkan pada gedung gereja tersebut akan menjadi hilang dan tidak berarti lagi.
Lantas, “Bagaimana sebuah objek dapat menjadi sakral?” Berkaitan dengan hal ini Durkheim menulis:
“ kekuatan religius tidak lain tidak bukan adalah perasaan-perasaan dalam diri setiap individu yang dipancing oleh kolektivitas, akan tetapi diproyeksikan ke luar pikiran yang mencerap dan mengobjektivikasinya. Agar bisa bisa diobjektivikasi, kekuatan tersebut harus melekat pada sesuatu yang kemudian menjadi sakral….Kesakralan yang dimiliki oleh sesuatu tidaklah muncul dari sisi intrinsik sesuatu tersebut: Kesakralan tersebut diimbuhkan padanya.”
Menjadi jelas disini, bahwa penetapan sakral atau tidaknya suatu objek tertentu sangat dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi kolektif yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat, lewat dominasi kolektifnya, bisa saja mengatakan bahwa binatang x itu sakral atau tumbuhan z itu sakral. Masyarakat memiliki kuasa untuk membuat objek-objek tertentu jadi sakral, sebab kualitas Yang Sakral hanya diimbuhkan atau ditambahkan saja pada objek-objek tertentu tersebut.
Oleh karena itu, Mariasusai mengatakan bahwa pembedaan antara Yang Sakral dan Yang Profan tidak akan benar-benar akan memisahkan mereka. Ia menulis:
“Dalam dan melalui yang profanlah yang kudus menyatakan diri. Dengan menampakkan kekudusan, objek apapun, disamping tetap seperti adanya, yaitu sebagai yang profan, ia menjadi sesuatu yang lain, yaitu yang kudus.”
Misalnya, ketika seekor binatang tertentu dianggap suci, “adanya” masihlah tetap sebagai seekor binatang. Ia tidak berbeda dengan binatang-binatang sejenisnya yang lain. Tetapi, ketika binatang tersebut menjadi objek yang suci, ia memperoleh kualitas yang disebut suci. Perubahan kualitas itulah, dari yang semula adalah seekor binatang biasa menjadi binatang suci, yang membedakannya dengan binatang-binatang biasa lainnya. Dalam hal ini, sekali lagi, konsensus yang ada dalam masyarakat ikut menentukan transformasi kualitas sebuah benda atau seekor binatang tertentu menjadi Yang Sakral, yang harus dihormati oleh banyak orang.
Totem(isme)
Secara sederhana, totem adalah simbol. Tapi, simbol apa? Totem adalah simbol dari kekuatan gaib yang disembah oleh anggota masyarakat atau klan tertentu.
Perwujudan totem biasanya mengambil bentuk dalam rupa binatang atau tetumbuhan yang memiliki hubungan organisasional khusus dengan masyarakat atau klan tertentu. Selain itu, pada saat yang sama, totem juga merupakan sesuatu yang konkret, yang menjadi gambaran nyata sebuah klan.
Secara analog, kita bisa membandingkan penggunaan totem dengan lambang atau logo sebuah perkumpulan tertentu. Kelompok sepak bola Malang, misalnya, menggunakan logo bergambar singa yang mengaum dengan latar berwarna biru. Jadi, ketika suatu saat kita melihat gambar singa yang mengaum dengan latar yang berwarna biru, ingatan kita langsung tertuju pada perkumpulan sepak bola yang direpresentasikan oleh gambar tersebut. Begitu pun halnya dengan totem. Totem merupakan simbol yang merepresentasikan kehadiran dari tuhan dan sekaligus juga melambangkan ciri-ciri suatu klan tertentu. Jadi, dengan demikian, totemisme memiliki fungsi ganda dalam kehidupan suatu klan. Ia tidak hanya sekadar berfunsi sebagai sosok yang disembah atau yang disakralkan oleh suatu klan tertentu. Tetapi, ia juga menjadi simbol atau lambang kelompok dan menjadi sarana pemersatu dalam klan tersebut.
Oleh karena itu, dalam pengamatan Durkheim, ia melihat bahwa setiap binatang atau tetumbuhan yang bukan totem boleh diburu atau dimakan, karena binatang atau tetumbuhan tersebut tidak melambangkan kekuatan gaib klan. Mereka termasuk dalam bagian dari Yang Profan. Tapi, tidak demikian halnya dengan binatang atau tetumbuhan yang dijadikan totem. Binatang atau tetumbuhan tersebut adalah bagian dari Yang Sakral, yang harus disembah, karena melambangkan kekuatan gaib klan, oleh karena itu, binatang atau tetumbuhan tersebut menjadi terlarang bagi seluruh anggota klan.
Lebih jauh, Durkheim berpendapat bahwa simbol-simbol yang dihadirkan dalam totem bukan hanya menjadi bagian dari Yang Sakral, tetapi juga merupakan perwujudan dan contoh yang sempurna dari Yang Sakral. Sebagaimana Durkheim menulis:
“…lambang-lambang totemik dapat dikatakan sebagai sebaga tubuh tuhan yang bisa diraba. Dari totemlah muncul aktus-aktus penghormatan atau ketundukan yang menjadi tujuan pemujaan…. Inilah sebabnya kenapa totem menempati posisi tertinggi dari susunan hal-hal yang sakral.”[6]
Sebagai perwujudan yang sempurna dari Yang Sakral, binatang atau tetumbuhan yang hadir dalam totem tersebut juga mengkomunikasikan kesakralannya kepada makhluk yang ada di sekelilingnya. Misalnya saja, ketika klan tertentu berkumpul untuk mengadakan upacara keagamaan, maka kita akan mendapati wujud dari totem yang hadir dalam beragam ukiran pada kayu atau batu, yang biasanya diletakkan di tengah tempat upacara. Tujuan dari pengukiran totem dan peletakkannya di tengah-tengah tempat upacara semata-mata hanya untuk menghadirkan perasaan kolektif diantara para anggota klan, bahwa sosok Yang Sakral, yang mereka sembah, ada dan hadir ditengah-tengah mereka.
Disamping itu, Durkheim juga melihat bahwa ritual-ritual keagamaan merupakan kesempatan yang luar biasa bagi anggota klan untuk mengukuhkan kelompok sosialnya. “Bagaimana hal itu bisa terjadi?” Ulasan Brian Morris tentang tulisan Durkheim menarik untuk disimak, ia mengatakan bahwa,
“Ketika individu-individu berkumpul untuk merayakan ritual-ritual keagamaan menyembah totem, muncul suatu kondisi emosional puncak, yang disebutnya dengan ‘delirium’ atau keriang-gembiraan kolektif, dimana klan atau kelompok sosialnya dikukuhkan.”
Lantas, “Seperti apa bentuk dari keriang-gembiraan kolektif itu?” Durkheim menulis:
“saat individu-individu dikumpulkan, terdapat semacam kekuatan listrik yang muncul dari kedekatan Antara mereka dan memindahkan mereka ke dalam keadaan pucak yang lain dari pada biasanya….maka dari segala penjuru yang ada hanyalah gerakan-gerakan liar dan kasar, teriakan, lolongan, dan suara-suara yang memekakkan telinga dari segala sesuatu yang bertujuan memperdalam tingkat intensitas perasaan yang diekspresikan….gestur dan teriakan-teriakan ini cenderung mengahasilkan bentuk yang ritmis dan teratur, dari sini kemudian berubah menjadi nyanyian dan tari-tarian.
Jadi, ritual-ritual penyembahan totem yang menghasilkan keriang-gembiraan kolektif dalam bentuk nyanyian dan tari-tarian tersebut tidak hanya berfungsi menguatkan ikatan religius seseorang dengan totem yang disembahnya, tetapi juga, sekali lagi, menguatkan ikatan yang melekatkan inividu kepada kelompok sosial dimana ia menjadi salah seorang anggotanya. Apalagi, dengan melakukan upacara-upacara ritual secara bersama-sama dan larut dalam keriang-gembiraan kolektif yang tercipta dari ritual tersebut, tiap individu merasa bahwa kehadirannya diakui, dilindungi, oleh kelompok dimana ia menjadi anggotanya.
Agama (Totem) dan Masyarakat
Dalam bagian awal buku “The Elementary Forms of the Religious Life,” Durkheim telah mengklaim bahwa,
“representasi-representasi religius adalah representasi-representasi kolektif yang mengungkapkan realitas-realitas kolektif; ritus-ritus merupakan bentuk tindakan yang hanya lahir di teng;ah kelompok-kelompok manusia dan tujuannya adalah melahirkan, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan-keadaan mental tertentu dari kelompok-kelompok itu.”
Nah, dalam pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa penyembahan terhadap tuhan atau dewa-dewa dalam masyarakat primitif adalah perkara bagaimana mereka mengekspresikan dan memperkuat kepercayaan mereka kepada klan. Dalam kesempatan itu, tiap orang telah menghilangkan diri pribadinya dan melebur ke dalam kerumunan massa. Lagi, mereka meninggalkan hal-hal yang mereka miliki dan menggabungkan identitas pribadi mereka ke dalam klan yang lebih besar. Sementara itu, dalam upacara-upacara ritual penyembahan totem, mereka pun juga menyatakan kesetiaan mereka kepada klan. Daniel L. Pals mengatakan bahwa,
“fungsi ritual keagamaan yang jauh lebih penting dari keyakinan ini akan memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk memperbaharui komitmen mereka kepada komunitas, mengingat bahwa dalam keadaan apapun, diri mereka akan selau bergantung kepada masyarakat, sebagaimana masyarakat juga bergantung pada keberadaan mereka.”
Dengan demikian, sekali lagi, dapat dikatakan bahwa totem atau agama merupakan sarana pembangkit perasaan sosial. Melalui simbol-simbol dan ritual-ritual, totem atau agama tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan perasaan mereka yang selalu terikat dengan komunitasnya.
Lebih jauh, klaim Durkheim yang mengatakan bahwa “agama adalah sesuatu yang benar-benar bersifat sosial” juga nampak dalam pemisahan antara hal Yang Sakral dengan hal Yang Profan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kualitas Yang Sakral hanya diimbuhkan atau ditambahkan saja pada objek-objek tertentu, misalnya binatang atau tetumbuhan yang dijadikan totem oleh masyarakat primitif. Lantas, “siapa yang berhak untuk menetapkan objek-objek tertentu itu masuk dalam kategori sakral atau tidak?” Tentu saja, masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang luar biasa besar untuk menetapkan apa, siapa, atau bagaimana perasaan-perasaan religius itu direpresentasikan dalam hidup keseharian dan hidup keagamaan masyarakat setempat.
Penutup
Teori agama yang digagas oleh Durkheim menunjukkan kepada kita bahwa agama itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terisolir dari masyarakat dimana ia berada. Agama itu selalu bersifat sosial, karena pada dasarnya ia lahir dari konsensus masyarakat terhadap apa yang dianggap religius atau sakral. Ia juga dianggap bersifat sosial karena dalam perayaan-perayaan keagamaan selalu hadir banyak orang yang secara bersama-sama membangun suasana mental tertentu, yang oleh Durkheim disebut sebagai “keriang-gembiraan kolektif.”
Nah, jika demikian, “Bagaimana dengan realitas keagamaan kita sekarang?” “Apakah realitas keagamaan kita sekarang masih menghadirkan sifat -sifat sosial dalam dirinya?” Jika kita sedikit menilik realitas hidup keagamaan kita, maka kita akan menemukan banyak sekali contoh yang meneguhkan klaim-klaim yang telah diajukan oleh Durkheim mengenai agama. Tengok saja kerumunan orang yang berkumpul disekitar dan/atau di dalam masjid, gereja, vihara, atau tempat-tempat peribadatan lainnya. Kerumunan orang terebut hadir disana untuk menyembah dan menghormati sesuatu yang mereka anggap sebagai Yang Transenden atau Yang Sempurna dari Yang Sakral, entah itu Allah, Tuhan, God, Dewa, Budha, dsb. Dan, melalui suasana mental tertentu yang mereka bangun, apa yang sakral dari agama tersebut menjadi semakin bernilai dan berarti kehadirannya.
Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa konsensus yang terjadi di antara merekalah yang memungkinkan terjadinya pemisahan antara hal-hal Yang Sakral dengan hal-hal Yang Profan. Misalnya, sebuah gedung yang sama model dan warnanya bisa saja akan menjadi gedung yang berbeda perlakuannya dari masyarakat. Karena, gedung yang satu ditulisi, disepakati, dan digunakan sebagai gedung gereja, sedangkan gedung yang lain yang ditulisi dan difungsikan sebagai restoran atau perkantoran. Jadi, dengan demikian, nyatalah bahwa tiap bentuk dari representasi keagamaan yang kita miliki saat ini merupakan bentuk ekspresi simbolis dari kenyataan-kenyataan dan/atau keinginan-keinginan yang ada di dalam masyarakat, seperti yang telah diklaim oleh Durkheim.







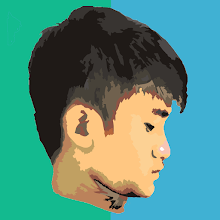


0 komentar:
Posting Komentar